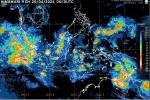OPINI
Penulis: Ulil Abshar-Abdalla
06:27 WIB | Senin, 17 Juni 2013
Karen Armstrong dan Tantangan Agama-Agama

SATUHARAPAN.COM - Ia memulai perjalanan spiritualnya, seperti pada umumnya para pemeluk agama manapun, dari tradisi yang sangat terbatas tradisi di mana ia lahir dan tumbuh besar: Katolik. Belakangan, ia keluar, tidak untuk menjadi seorang ateis atau agnostik, melainkan berusaha untuk merangkul tradisi-tradisi spiritualitas lain.
Kini ia bahkan menjadi juru khotbah bagi pentingnya membangun jembatan dan titik temu antar berbagi tradisi-tradisi itu. Ia mengajak kita untuk melupakan sejenak dimensi luaran dalam tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda-beda, seraya mencari nilai utama yang menjadi sari-pati dari kesemua tradisi terebut. Sari pati itu ia rumuskan dalam Hukum Emas (Golden Rule): Jangan engkau perbuat kepada orang lain sesuatu yang engkau tak suka orang lain perbuat pada dirimu. Secara sederhana, nilai itu ia beri nama kasih sayang atau compassion.
Orang itu Karen Armstrong, perempuan Katolik keturunan Irlandia yang pernah, selama tujuh tahun, menjadi biarawati pada sebuah ordo bernama Sisters of the Holy Child Jesus. Kecewa dengan kehidupan biarawati, ia kemudian meninggalkan ordo itu dan menempuh kehidupan keimanan yang independen dan bebas. Ia tidak meninggalkan agama, tetapi justru mencari kesamaan spiritual yang mempersamakan agama-agama. Ia menuai popularitas pertama kali melalui bukunya A History of God yang terbit pada 1993.
Saat terjadi peristiwa 9/11 di New York yang memicu kebecian dan purbasangka yang luas di Barat terhadap Islam dan umat Islam, Karen Armstrong mencoba mengoreksi fobia dan ketakutan pada Islam dengan menulis biografi tentang Nabi Muhammad yang terbit pada 2006 berjudul Muhammad: A Prophet of Our Time. Dalam buku itu, Armstrong mencoba menggambarkan Nabi sebagai figur reformis yang melakukan sejumlah reformasi sosial terhadap masyarakat Arab pada zamannya, juga sebagai figur politik yang mencoba membangun sebuah polity, bukan sekedar komunitas moral belaka. Lensa yang dipakai Karen Armstrong dalam melihat Muhammad bukanlah lensa kebencian, melainkan simpati dan compassion.
Tak kurang dari dua puluh lima buku telah lahir dari tangan Armstrong. Semuanya menggambarkan upaya dia yang sungguh-sungguh untuk making sense of religion, memahami agama-agama, serta menemukan mutiara terpendam yang mungkin berguna untuk mengobati sejumlah penyakit-penyakit kronis dalam masyarakat modern.
Perhatian Armstrong bukan saja terbatas pada ketiga agama-agama Abrahamik (Yahudi, Kristen, Islam), tetapi juga agama-agama Timur. Ia menulis sebuah buku menganai Buddha (2001). Baginya, sumbangan agama Timur terhadap pengayaan khazanah spiritualitas manusia tak kurang nilainya dibandingkan dengan agama-agama misionaris dari lingkungan tradisi semitik.
Dari keseluruhan buku dia, tampak benang yang kuat: perhatian pada dimensi mistik agama-agama; dimensi yang dalam Islam disebut dengan al-bathin. Dari sudut lahiriah, tentu saja ada banyak perbedaan, kadang ekstrim, antara agama-agama begitu ekstrimnya sehingga bisa berujung pada perang. Armstrong mecoba memahami dimensi yang membingungkan dari agama-agama ini, yakni dimensi kekerasan, dalam bukunya yang berjudul The Battle for God (2000) sebuah karya yang mencoba menelaah fenomena fundamentalisme dalam agama-agama, terutama Yahudi, Kristen dan Islam.
Tetapi pada tataran yang lebih dalam, tataran al-bathin, ada kesamaan antara agama-agama itu. Titik temu ini ia rumuskan dalam sebuah ajaran etis compassion, kasih sayang. Sejak 2009, ia meluncurkan gerakan global yang ia namai Charter for Compassion. Puluhan ribu tokoh dan individu dari perbagai kawasan dunia memberikan sokongan atas inisiatif ini.
Saya menganggap, dakwah yang sedang dilancarkan Armstrong ini tepat waktu, sekaligus tepat sasaran. Ada banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini. Dua di antaranya sangat mendesak. Pertama adalah problem kemiskinan dan kesenjangan kaya-miskin yang, dengan seluruh pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang cepat saat ini, masih terus menghantui kita. Kedua, adalah problem bigotry dalam bentuknya yang bermacam-macam. Bigotry adalah kebencian kepada orang lain dengan identitas kultural atau keagamaan yang berbeda.
Di Indonesia sendiri, kedua masalah ini masih juga menghantui kita hingga sekarang. Kemiskinan dan problem keadilan masih belum mendapatkan solusi yang tepat. Sementara itu, tendensi ke arah eksklusivisme dan pandangan-pandangan keagamaan yang sempit juga merebak di masyarakat, bahkan difasilitasi oleh keterbukaan politik yang kita nikmati setelah era reformasi.
Dalam konteks ini, compassion berarti dua hal: simpati dan solidaritas kepada mereka yang miskin dan tersingkirkan, serta kesediaan untuk mereka yang berbeda. Melalui gerakan Charter for Compassion, Armstrong hendak membawa nilai kasih sayang ke dalam fokus utama perhatian agama-agama. Kerapkali pemeluk agama lupa diri dan terlena dalam kesyahduan dan kesalehan individual, pemujaan berlebihan kepada kebenaran sendiri seraya menampik kebenaran-kebenaran di luar dirinya, atau terlena dalam pernik-pernik ritual dan legalisme-formalistik yang dapat mengaburkan esensi agama.
Di tengah-tengah konservatisme masyarakat Islam di Indonesia yang saat ini gampang mencurigai yang lain, mencemberuti gagasan pluralisme (ingat: pembedaan sembrono yang dibuat MUI antara pluralisme dan pluralitas, padahal keduanya saling terkait), suara Karen Armstrong kita perlukan. Selamat datang, bu Karen!
*Penulis adalah cendekiawan Muslim dan pengurus DPP Partai Demokrat.
BERITA TERKAIT
KABAR TERBARU

Bertemu Herzog, Menlu Inggris: Jelas Israel Akan Tanggapi Se...
YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, mengatakan jelas bahwa Israel...