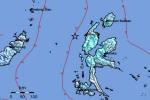Kuasa Wacana dan Bayang-bayang Kekerasan

SATUHARAPAN.COM - Belum lama ini seorang sahabat mengirimkan tautan berita lewat media Whatsapp. Isi berita itu cukup membuat mata terbelalak: seorang menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK menyebut kelompok minoritas LGBT (Lesbian, Gay, Bi-sexual, Trans-gender) sebagai bagian dari cuci otak murah-meriah perang modern pihak asing untuk menguasai Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia dalam keadaan darurat perang (modern), dan keberadaan kelompok LGBT adalah salah satu penyebab kedaruratan itu. Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa kelompok LGBT adalah musuh negara.
Saya sendiri bukan orang yang rajin mengikuti berita-berita di televisi, radio, atau jejaring media sosial. Saya jarang membaca koran, jarang menonton berita di televisi apalagi update media sosial. Berita-berita umumnya saya peroleh berkat jasa baik para sahabat yang mengirimkan berbagai tautan. Mungkin mereka merasa prihatin dengan orang-orang seperti saya yang bersikap cuek terhadap masalah-masalah dan gosip-gosip kekinian. Saya sendiri tidak tahu mengapa tiba-tiba pemberitaan media penuh sesak dengan persoalan LGBT, dan saya juga tidak tahu persisnya sejak kapan persoalan itu ramai dibicarakan. Namun berita dan pernyataan yang saya baca saat itu terasa cukup mengejutkan dan menyimpan sesat wacana.
Bayang-bayang Kekerasan Wacana
Pertama, pernyataan itu datang dari seorang menteri yang mewakili otoritas penyelenggara negara. Artinya, kata-katanya dapat dijadikan acuan wewenang untuk menerapkan berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri, yang dapat dijadikan dalih untuk menciptakan stabilitas nasional dan menindak mereka yang dianggap sebagai musuh negara. Kedua, pernyataan perihal kelompok LGBT tersebut secara langsung merupakan pernyataan politik yang datang dari seorang tokoh politik (dan tokoh militer). Setiap pernyataan politik selalu membawa bersamanya konsekuensi etis dan potensi konflik yang serius, apalagi jika datang dari para tokoh yang membawa di belakangnya basis-basis massa tertentu.
Persoalan dalam banyak pernyataan-pernyataan politik di ruang publik seringkali tidak terletak dalam isi persoalan yang dibahas (dalam hal ini LGBT), tetapi lebih terletak dalam cara bagaimana kekuasaan merumuskan dan melihat dirinya sendiri, melihat wewenangnya, dan melihat pihak-pihak lain di luar dirinya (Michel Foucault, 1980: 86-87). Dalam arti yang lebih luas kekuasaan bisa berarti negara, partai politik, kelompok mayoritas, tokoh masyarakat, agama, budaya, media massa dan jejaring media sosial, kelompok akademis, aliran politik, dan lain sebagainya.
Rupanya, dari berbagai wacana sosial-politik yang muncul akhir-akhir ini, termasuk soal LGBT dan surat edaran/larangan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), terlihat bahwa kekuasaan masih selalu mendefinisikan dan menegaskan dirinya dengan cara yang mengkhawatirkan, yaitu: melalui cara eksklusi (exclusion) atau meniadakan / menihilkan keberadaan pihak lain yang dirasa berbeda, asing, berbahaya dan mengancam. Demi keberlangsungan dirinya kekuasaan melipat-gandakan diri dengan terus-menerus menciptakan musuh-musuhnya.
Pola-pola pendefinisian kekuasaan seperti ini mungkin bersumber dari sesat pemahaman atas diri kita sendiri. Mungkin saja kita terlalu terbiasa menegaskan keberadaan diri kita dengan memutlakkan-diri dan merelatifkan keberadaan orang lain. Apalagi jika motif-motif pemutlakkan-diri ini semakin tersamarkan di balik slogan-slogan moral, agama, dan nasionalisme. Bahkan kita mungkin semakin senang dengan diri kita jika bisa menginjakkan kaki dan berdiri tegak di atas kepala orang lain.
Tetapi apapun itu, perlu disadari bahwa di wilayah ruang publik, setiap pernyataan dan perkataan memiliki konsekuensi etis dan implikasi politik yang tidak main-main. Sebab, setiap perkataan dan pernyataan di ruang publik bisa bergulir cepat jauh melampaui intensi awal mereka yang memberikan pernyataan. Pernyataan perihal LGBT misalnya memiliki konsekuensi etis dan implikasi politik yang tidak lagi berkenaan dengan persoalan LGBT itu sendiri, melainkan dapat meluas tak terbatas dipelintir sedemikian rupa sesuai kepentingan tertentu. Jika kelompok LGBT dianggap sebagai sesat, tidak bermoral, mengancam stabilitas, dan karena itu menjadi ‘musuh bangsa-negara’, maka kata ‘LGBT’ sebetulnya bisa diganti dengan apa saja dan siapa saja.
Berbagai kelompok yang dianggap berbahaya dan tidak disukai kekuasaan bisa kapan saja masuk menggantikan tempat ‘LGBT’, seperti misalnya: seniman dan musisi, kalangan akademis, sanggar-sanggar kebudayaan, para jurnalis dan reporter, pedagang asongan, kelompok agama tertentu, atau siapa saja. Maka, orang seperti saya misalnya, yang mungkin secara pribadi tidak setuju dengan posisi moral kelompok LGBT, justru menjadi bersimpati karena persoalan telah jauh keluar dari porsi yang semestinya dan meluas ke sana-sini. Yang lebih mengkhawatirkan, jika kelompok dan/atau pribadi-pribadi tertentu telah secara publik terkena stigma sebagai ‘musuh negara’, ‘musuh ideologi’, ‘aliran sesat’, ‘berbahaya’ yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka mereka dengan sendirinya telah ditempatkan dalam posisi rawan sebagai sasaran kekerasan struktural dan kekerasan sosial. Dan ujung terjauh dari segala kekerasan tidak lain adalah kematian, termasuk juga kematian akal sehat dan kewarasan kita.
Kuasa dalam Wacana
Filsuf Michel Foucault, tokoh aliran pasca-strukturalis Prancis, menyebut bahwa kita semua menyimpan di kepala kita benih fasisme, entah kita seorang agamis, seorang moralis, seorang nasionalis, seorang Marxis, atau seorang yang demokratis (Michel Foucault, 1980: 99). Sebab, kita selalu menjadi bagian dari pola relasi kekuasaan (dan kekerasan) tertentu yang darinya kita tidak dapat lolos. Artinya, dalam diri kita masing-masing terdapat motif kuasa-menguasai yang bekerja hingga ke tingkat paling mikro dalam hidup keseharian. Ini juga berarti setiap kata yang terucap dan wacana yang tercipta merupakan bentuk pembadanan motif kekuasaan yang tertentu. Bahasa dan wacana memiliki daya kuasanya tersendiri.
Daya kuasa dalam bahasa dan wacana ini justru sering lebih mematikan dari moncong senjata sebab daya itu bekerja dalam rutinitas keseharian secara tidak disadari. Daya kuasa wacana juga selalu bersifat paradoksal dan ambigu sebab daya itu dapat mendamaikan tetapi juga membakar, membuat orang peduli tetapi juga memantik hasrat membunuh, menggelorakan rasa solidaritas tetapi juga mengobarkan rasa benci. Ini juga sebab mengapa sejarah bangsa-bangsa modern memperlihatkan bahwa setiap peristiwa kekerasan selalu didahului oleh pembentukan dan penggiringan wacana tertentu yang semakin mengkristal jauh sebelumnya (Wilhelm Reich, 1946: 180-181).
Maka setiap wacana selalu memiliki daya kuasanya yang tertentu, apalagi jika wacana itu muncul dari para tokoh atau para pejabat negara. Oleh karena itu menjadi tanggungjawab etis dan tugas politis setiap warga, apalagi para tokoh bangsa dan instansi negara, untuk mengisi wacana publik dengan muatan kata yang tepat konteks dan muatan bahasa yang tepat nalar. Jika seseorang tidak sungguh memahami perihal suatu peristiwa yang sedang terjadi, maka sebaiknya orang itu tidak perlu cepat-cepat memberi komentar, atau bahkan lebih baik tidak berkomentar sama sekali, bahkan jika ia seorang petinggi negara atau tokoh internasional sekalipun. Sebab kata yang telah terucap bisa terangkai menjadi rentetan peristiwa tersendiri. Dan setiap peristiwa selalu menyimpan potensi konflik kekerasan baik di masa kini atau pun di masa depan. Hanya jika kita siap menerima konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh kesewenangan wacana, maka barulah kita bisa berbicara berkomentar sesuka hati kita di ruang publik. Tentu konsekuensi fatal yang akan selalu membayangi kita adalah kehancuran bahkan kematian hidup orang lain yang terdampak oleh wacana tersebut.
Mungkin pada akhirnya, di tengah silang-sengkarut wacana ruang publik, kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing mengapa kita begitu mudah terganggu dengan berbagai hal yang kita anggap berbeda, berbahaya dan mengancam? Betulkah hal-hal itu sungguh mengancam keberadaan diri kita? Atau jangan-jangan, kita membenci dan memusuhi orang lain atau kelompok tertentu bukan karena mereka mengancam, tetapi karena kita harus melakukan itu demi menutupi kelemahan dan kekosongan diri kita sendiri? Semoga tidak sampai terjadi kekhawatiran bahwa atas nama panji-panji moral ternyata kita justru sedang perlahan-lahan meruntuhkan fondasi moral ruang publik demokratis yang telah kita bangun bersama selama ini.
Penulis adalah anggota Lingkar Studi Terapan Filsafat
Editor : Trisno S Sutanto

Trump Usul AS Kendalikan Jalur Gaza, Bahas Rencana Perdamaia...
WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Pernyataan mengejutkan dari Presiden Donald Trump bahwa ia ingin Amer...